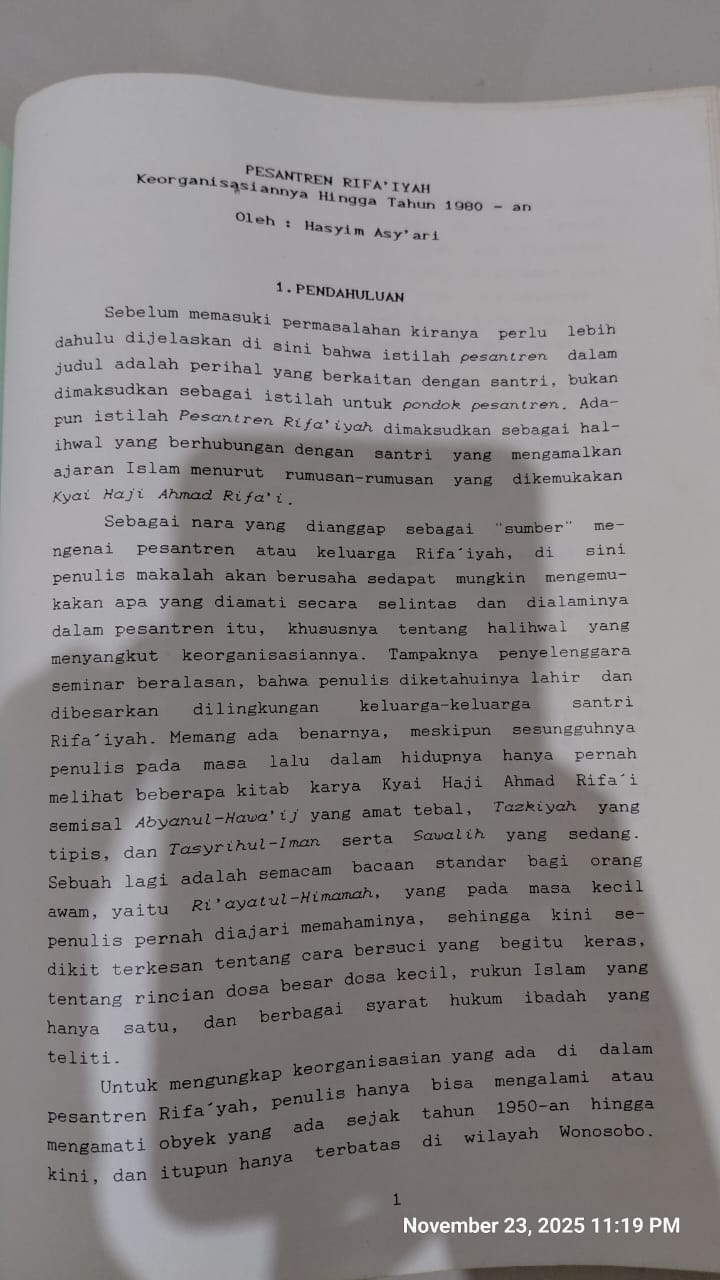Pendahuluan
Sebelum memasuki permasalahan kiranya perlu lebih dahulu dijelaskan di sini bahwa istilah pesantren dalam judul adalah perihal yang berkaitan dengan santri, bukan dimaksudkan sebagai istilah untuk pondok pesantren. Adapun istilah Pesantren Rifa’iyah dimaksudkan sebagai hal-ihwal yang berhubungan dengan santri yang mengamalkan ajaran Islam menurut rumusan-rumusan yang dikemukakan Kyai Haji Ahmad Rifa’i.
Sebagai nara yang dianggap sebagai “sumber” mengenai pesantren atau keluarga Rifa’iyah, di sini penulis makalah akan berusaha sedapat mungkin mengemukakan apa yang diamati secara selintas dan dialaminya dalam pesantren itu, khususnya tentang ihwal yang menyangkut keorganisasiannya. Tampaknya penyelenggara seminar beralasan, bahwa penulis diketahuinya lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga-keluarga santri Rifa’iyah. Memang ada benarnya, meskipun sesungguhnya penulis pada masa lalu dalam hidupnya hanya pernah melihat beberapa kitab karya Kyai Haji Ahmad Rifa’i semisal Abyanal-Hawa’ij yang amat tebal, Tadzkiyah yang tipis, dan Syarihul Iman. Sebuah lagi adalah semacam bacaan standar bagi orang awam, yaitu Ri’ayatul Himmah, yang pada masa kecil penulis pernah diajari memahaminya, sehingga kini sedikit terkesan tentang cara bersuci yang begitu keras, tentang rincian dosa besar dosa kecil, rukun Islam yang hanya satu, dan berbagai syarat hukum ibadah yang teliti.
Untuk mengungkap keorganisasian yang ada di dalam pesantren Rifa’iyah, penulis hanya bisa mengalami atau mengamati obyek yang ada sejak tahun 1950-an hingga kini (1990), dan itupun hanya terbatas di wilayah Wonosobo.
Obyek itu diharapkan tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di wilayah-wilayah lain, terutama di Jawa Tengah. Meskipun demikian, karena kini telah ada literatur-literatur mengenai pesantren Rifa’iyah, pembatasan obyek seperti disebut di muka lebih bisa diperluas medannya.
Tulisan-tulisan mengenai pesantren Rifa’iyah kini mulai terlihat semakin banyak, namun yang merupakan kesatuan bulat mencakup berbagai aspeknya, menurut hemat penulis, adalah sebuah karya Adaby Darban, Rifa’iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah th. 1850–1982 (1987). Karya ini menjadi acuan utama dan sekaligus untuk mencocokkan apa yang dialami dan dilihat penulis dalam kehidupan pesantren Rifa’iyah.
Rifa’iyah dalam Keorganisasian Tradisional
Dalam mewujudkan cita-cita kemasyarakatannya, sebagai homo socius, manusia mempunyai kecenderungan mengajak sesamanya untuk memikul tanggungjawab demi keberhasilannya. Dengan demikian pembentukan perkumpulan, jamaah, ataupun organisasi, merupakan sesuatu yang inheren (fittry, salikiy) pada manusia. Kyai Haji Ahmad Rifa’i dalam kedudukannya sebagai ulama, terlebih lagi, tentunya juga telah menyadari hal yang demikian itu, apapun wujudnya. Wadah atau sarana apa yang ia gunakan untuk mencapai cita-citanya, dengan tulisan ini, diharapkan dapat sedikit terungkap keberadaannya.
Dapat diyakini bahwa para murid Kyai Haji Ahmad Rifa’i sendiri tidak pernah menyebut ikatan sesamanya sebagai sekte budiyah, Gerakan Rifa’iyah, Santri Salak, Santri Ngelmu Kalisalak, dan sejenisnya dari sebutan yang wajar hingga terlebih lagi yang berupa sinisme. Istilah-istilah tersebut lebih bisa dipastikan pada mulanya datang dari luar kalangan mereka. Pada mulanya paling mungkin mereka hanya menyebut diri atau kelompoknya sebagai murid Kyai Haji Ahmad Rifa’i atau yang semacam itu. Meskipun demikian, paling tidak pada tahun 1950-an, istilah Wong Tarajumah atau Santri Tarajumah sudah beredar luas dan diakui de facto oleh para pengikut ajaran Kyai tersebut, untuk membedakannya dengan saudaranya kaum muslim yang lain yang biasa mereka sebut sebagai santri ngadat, santri menurut adat. Baru setelah didirikannya Yayasan Pendidikan Islam Rifa’iyah (YPIR) pada 7 Mei 1965 istilah Gerakan Rifa’iyah mulai ramai terdengar di dalam maupun di luar kalangan warga Santri Tarajumah. Istilah yang telah mapan ini kadang-kadang memang tidak mudah ditelusur awal mulanya, seperti halnya istilah Daulah Islamiyah, misalnya, kapan secara formal dipakai oleh sebuah negara masih perlu ditelusur secara cermat.
Nama Kyai Haji Ahmad Rifa’i, dalam beberapa dokumen dan literatur kadang-kadang disebut agak berbeda, seperti misalnya Kaji Ripangi menurut Serat cebolok karena ditulis dengan huruf Jawa. Dalam dokumen Belanda ditulis Hadjiie Mohamad Rafangie, Chadjie Achmad Ripangie, atau Hadjiie Mohamad Rafangie. Bagi para peneliti mungkin perbedaan-perbedaan ini dapat digunakan seperlunya. Pendiri pesantren Rifa’iyah sendiri dalam kitab-kitabnya biasa menyebut nama dirinya Haji Ahmad Rifa’i ibni Muhammad, tanpa menyebut gelar Kyai di depannya. Ia lahir tahun 1786 di wilayah Kendal, bermukim di Kalisalak Limpung Batang, dan meninggal di Tanah Tondano, Minahasa, Manado, Sulawesi Utara. Masa hidupnya pada abad 19 itu adalah masa kebangkitan kembali umat Islam setelah lenyapnya Abbasiyah dan melemahnya Turki. Dengan demikian tentunya ia mendengar gema pembaharuan masyarakat Islam Muhammad Ali (1769–1849) di Mesir, gema Wahabiyah di Jazirah Arabia, dan Perang Diponegoro di Jawa (1825–1830).
Pada masa-masa itu umat Islam mulai sibuk berbenah menghadapi bahaya yang semakin menantang dari Barat yang didukung kemajuan teknologi, militer, politik, dan ekonomi. Pada masa itu tampaknya merupakan yang pertama kali pengalaman bagi umat Islam, bahwa ancaman fisik dan idiologi datang sekaligus pada saat dan asal yang sama, yang sebelumnya tidak pernah demikian.
Begitulah Kyai Haji Ahmad Rifa’i muncul menanggung beban ketidakpuasan terhadap keadaan yang dihadapinya. Tekanan politik pemerintah kolonial dengan akibat merosotnya kualitas idiologi Islam amat ia rasakan. Tentunya ia sadar bahwa melawan politik kekuasaan Belanda secara terbuka akan sia-sia, karena ia tahu bahwa Pangeran Diponegoro saja, yang hidup sezaman dengannya, kalah menghadapi Belanda. K.H. Ahmad Rifa’i seorang ulama yang tak bersenjata, maka tidaklah mengherankan jika ia merasa lebih bertanggung jawab terhadap ancaman idiologi daripada politik akibat kekuasaan asing itu.
Untuk itu ia tampil dengan apa yang telah diperoleh dengan ilmu agamanya, berfatwa, mengumpulkan murid, yang selanjutnya dengan sendirinya terbentuklah sebuah ikatan jamaah sebagai bentuk organisasi tradisional yang sederhana tetapi cukup efektif. Sesuai dengan jaman dan lingkungannya, ia bentuk poros imam-umat, guru-murid sebagai sendi organisasi tradisional Islam, dengan tujuan yang dapat diringkas sebagai membentuk kader pemimpin alim-adil dan masyarakat baru yang mukmin muslim yang berani mengatakan kebenaran dan kepribadian.
Pada awal kegiatannya, disamping mengadakan pengajian-pengajian untuk masyarakat umum (wong ngawam), ia mencetak badal yang merupakan kader masa depan. Pada waktu itu telah tercatat sekitar 13 orang badal terkemuka yang ia bina, dan mereka itu adalah Arfani alias Abdul Aziz dari Sapuran Wonosobo; Kurdi alias Abu Hasan dari Kepil Wonosobo (asal Purworejo); Muhammad Toyib dari Kalibaru Batang; Abdul Hadi dari Kretek Wonosobo; Abu Mansyur dari Sapuran Wonosobo; Ishak dari Sapuran Wonosobo; Hadits dari Karangsambo; Munawir dari Wanabadra Batang; Ilham dari Kalipucang Batang; Abdul Kohar dari bekinging Kendal; Abdul Fatah dari Sikidang Wonosobo (dekat Donorejo); Muhammad Tubo dari Purwosari Kendal; dan Imam Pura (Maufuro) menantu Kyai dari Kalisalak Limpung Batang. Dari anak cucu mereka sedikit banyak dapat diperoleh bahan-bahan tentang Rifa’iyah, dan sebagian besar mereka masih mudah dijumpai.
Pada Badal itu diserahi tugas menyalin kitab-kitab tarajumah dan menyebarluaskan kandungannya. Kalau pada waktu itu hanya kitab-kitab agama masih langka dan umumnya berbahasa Arab sehingga kurang melancarkan penyiaran agama dengan media tulis, maka sesungguhnya jasa para badal itu amat besar dalam berbagai hal. Tradisi menyalin kitab-kitab itu berlanjut hingga kini.
Setelah K.H. Ahmad Rifa’i dibuang ke Ambon tahun 1859, para badal terus melanjutkan ajaran Kyai secara damai, hanya saja menantunya, Imam Puro, karena terus mendapat tekanan dari Belanda ia pergi haji dan tidak pulang ke Kalisalak, tetapi menetap di Singapura sampai meninggal (namun disampaikan beliau bahwa data yang sesuai adalah saat proses pulang haji dan sampai di Singapura, beliau meninggal). Para murid kemudian membentuk ikatan-ikatan persaudaraan yang diperkuat dengan saling menikahkan keluarganya dengan keluarga di wilayah lain yang hal itu telah diberi contoh Kyai yang mengambil Imam Puro, muridnya, sebagai menantu. Tradisi demikian juga masih terasa hingga kini, sehingga pesantren Tarajumah seakan-akan sebagai sebuah keluarga besar yang saling berhubungan nasab.
Pada awal abad ke-20 ikatan pesantren warga Rifa’iyah makin maju pesat dengan damai, tidak galak seperti ketika Kyai masih hidup, demikian pula pondok-pondoknya makin bertambah. Laporan-laporan dari asisten Residen Wonosobo dan Kendal kepada atasannya tahun 1924 menunjukkan situasi ketenangan itu, tanpa adanya hal-hal yang mengarah kepada gejolak.
Pada masa itu pula muncul tokoh-tokoh Rifa’iyah generasi baru, seperti di Lampung Batang K.H. Hasan Mubari, di Kalipucang Batang K. Imam Haji, di Kedungwuni Pekalongan K. Saleh, di Kendal K.H. Idris, di Kayen Pati K. Shidiq, dan di Kertek Wonosobo K. Hasan Markam. Di samping mereka masih ada lagi yang sempat dicatat pemerintah Belanda, yaitu tokoh-tokoh seperti K. Kasbullah di Temonduwur Sapuran Wonosobo yang sangat alim menguasai 51 kitab Tarajumah. Selain itu adalah K.H. Ahmad Badri bin Idris dari Purwosari Patebon Kendal, K. Nasipan dari Bayutawa Kendal, K.H. Shidiq Karangmalang Weleri, K.H. Amin Siwalan Bulak Weleri, K. Umar Said Aram-Aram Bulak Weleri, dan K. Sarbun Cepaka Gemuk Weleri. Yang agak meloncat jauh adalah K. Taabut dari Sepatkerep Cimalaya Batavia. “Koloni” santri Tarajumah Cempakah Putih Jakarta yang ada sekarang belum jelas apakah mereka anak cucu kelompok K. Taabut ini atau tidak.
K. Mad Said dari Cepaka Gemuk Weleri agak unik, karena ia mempunyai ijin resmi mengajar Tarajumah dari pemerintah Belanda. Mungkin sekali kitab-kitabnya telah disensor terlebih dahulu oleh pemerintah sehingga ajaran-ajaran yang membahayakan bisa dihindari.
Dapat ditambahkan di sini bahwa seperti dalam masyarakat muslimin yang lain, warga santri Rifa’iyah juga mempunyai semacam unit-unit kerja yang ketuanya ditunjuk oleh Kyai setempat yang mengurus kegiatan tertentu. Unit kesenian pun ada, tetapi tentu saja yang berkaitan dengan ketarajumahan semacam unit Solawatan Jawa atau Ayun-ayun yang dengan terbang besar tanpa kendang (karena dianggap haram) mengalunkan (ngeliki) puisi-puisi yang ada pada kitab Tarajumah. Unit al-Barzanji pada dasarnya tidak dikenal, karena dianggap kebudayaan Santri Ngadat. Wayang, ketoprak, gendingan, orkes, semuanya diharamkan karena dianggap lagha (sia-sia, tak ada gunanya). Dalam hubungan dengan hari besar Islam, selain untuk led, unit kerja untuk peringatan Isra’ Mi’raj cukup menonjol karena di situ dibacakan kitab K.H. Ahmad Rifa’i yang bernama Kitab Arja (80 halaman). Peringatan Maulid Nabi tidak menonjol bahkan sering ditiadakan, atau tidak ada, mungkin untuk membatasi ritualisme, sehingga pada masa umumnya orang Islam suka pada banyak upacara-upacara, santri Tarajumah agak kelihatan minimalis. Sementara itu dalam perjalanan pesantren Rifa’iyah, tanpa tersadari telah menampilkan semacam sub-kultur santri tersendiri yang refleksi kulturnya nampak dalam hal bersikap, berpakaian, dan hal-hal lain yang hanya bisa dirasakan oleh warga Tarajumah maupun warga lain yang tiap hari melakukan kontak sosial dengan mereka.
Rifa’iyah dalam keorganisasian Modern
Sekitar pertengahan abad ke-20 atau tahun 1950-an, kehidupan partai-partai politik di Indonesia makin ramai keberadaannya. Sebagai organisasi modern yang umumnya datang dari pusat pemerintahan, pengaruhnya amat kuat sampai ke desa-desa karena adanya rapat-rapat kampanye. Kegiatan partai-partai Islam amat berpengaruh terhadap dinamika kaum muslimin di seluruh pelosok tanah air. Isu-isu yang mengkontraskan ajaran Rifa’iyah dan yang bukan menjadi tertelan oleh arus semangat kepartaian. Meskipun demikian hal itu tidak mempengaruhi keberadaan dan dinamika pesantren Rifa’iyah, walaupun mereka tidak membentuk organisasi modern untuk wadah aspirasinya.
Warga Rifa’iyah baik secara pribadi maupun berkelompok memasuki partai politik sesuai dengan keinginan masing-masing. Tokoh Rifa’iyah K.H. Mastur misalnya, ikut aktif memimpin PSII wilayah Pekalongan. Gurunya K.H. Mubari, bahkan telah ikut aktif menjadi pengurus SI Pekalongan sejak masa sebelum itu.
Ketika kelompok-kelompok politik Islam bergabung dalam Masyumi, dapat dipastikan semua warga Rifa’iyah adalah anggotanya. Setelah partai itu pecah pada awal 1950-an, mereka terpencar, ada yang masuk NU, PSII, atau tetap di Masyumi. Warga Rifa’iyah yang masuk Muhammadiyah, sepanjang pengalaman penulis, umumnya bergabung sesudah tahun 1960-an, yaitu sesudah Masyumi dibubarkan, sedangkan mereka hingga tahun itu adalah anggota Masyumi. Di wilayah Wonosobo ada pula sementara warga Rifa’iyah yang masuk PNI karena tokoh-tokohnya menjadi pamong desa atau lurah, sedangkan waktu itu PNI menguasai Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Penerangan, dsb. Sesudah tahun 1970-an umumnya mereka masuk Golkar atau PPP.
Di bidang pendidikan, sesudah tahun 1950-an juga timbul suatu fenomena baru bagi warga pesantren Rifa’iyah. Sekolah-sekolah dasar yang dibangun pemerintah mulai menjamur, dan madrasah-madrasah Islam yang dikelola secara modern juga makin banyak di pedesaan. Hal ini terasa sekali mengurangi laju pondok-pondok pesantren Rifa’iyah yang masih tradisional itu. Anak-anak warga Rifa’iyah mulai banyak memasuki sekolah-sekolah modern baik umum maupun agama. Sejak itu sebagian generasi baru warga Rifa’iyah jauh dari kehidupan Tarajumah, dan bahkan sebagian lagi sudah tidak mengenal. Meskipun demikian sebagian lain masih merasa sebagai warga Tarajumah, bahkan merasa prihatin terhadap keadaan kehidupan “kultur” ketarajumahan yang makin dijauhi anak-anaknya sendiri. Dari mereka inilah timbul gagasan untuk memodernisasikan pendidikan yang telah diwariskan K.H. Ahmad Rifa’i, dan muncullah Yayasan pendidikan Islam Rifa’iyah pada tanggal 7 Mei 1965/7 Muharram 1384 H. atas rintisan seorang pemuda guru agama di desa Tanahbaya Randudongkal Pemalang. Bersama kawan-kawan dan ulama yang mendukungnya muncullah Tjarbin memimpin yayasan itu hingga lahir sekolah-sekolah yang dikelola berdasar keorganisasian modern, dan hidup hingga kini. Kalau organisasi ini tampak kurang maju dengan cepat, kiranya bisa dimaklumi karena daya dukung masyarakat pedesaan memang belum kuat. Tetapi suatu hal yang menarik dan patut mendapat penghargaan adalah bahwa organisasi ini muncul dari desa, berpusat di desa jauh dari kota, tetapi mempunyai jaringan yang cukup luas, dan cukup berpengaruh dalam masyarakat Rifa’iyah bahkan berpengaruh di Jakarta.
Hingga tahun 1980-an putra-putra warga Rifa’iyah telah amat banyak yang menjadi mahasiswa, warga yang masih mengenal ketarajumahan maupun yang sudah tidak tahu menahu. Oleh karena itu pada bulan Mei 1988 di Limpung Batang pernah dirintis adanya Forum Komunikasi Mahasiswa Rifa’iyah (FKMR) yang tokohnya antara lain Mursidin Romly dan Slamet Siswadi. Keduanya, dan sebagian besar perintis FKMR lainnya, adalah para mahasiswa dari IAIN Walisongo Semarang. Kelanjutan usaha perintisan adanya forum itu sekarang masih belum jelas mengingat adanya banyak kendala, antara lain karena perkumpulan itu ingin muncul bukan karena adanya angin dari atas. Sebagaimana gerakan K.H. Ahmad Rifa’i yang bisa diklasifikasikan sebagai Rural Movement, maka mungkin juga usaha mewujudkan FKMR itu juga sebagai “Rural” student movement yang jarang ada di Indonesia.
Mungkin dapat ditambahkan di sini mengenai pandangan ulama Rifa’iyah sendiri terhadap Yayasan Pendidikan Islam Rifa’iyah (YPIR), bahwa mereka banyak yang mendukung tetapi banyak pula yang tidak. Hal ini mudah diperkirakan sebabnya, yaitu bahwa setiap perubahan akan membuat kegoncangan terhadap kemapanan.
Kesimpulan
Untuk menuju kata akhir mungkin lebih baik untuk disebutkan lagi bahwa K.H. Ahmad Rifa’i tampil lebih banyak untuk melawan ancaman ideologi daripada melawan ancaman politik yang datang dari penjajah. Dalam mewujudkan cita-citanya itu ia lebih suka menggunakan pena dan mengajar yang kekuatannya tidak kalah ampuh daripada dengan yang lainnya. Dengan tulisannya yang lebih dari 50 kitab itu berarti ia seorang penulis besar untuk abad itu, dan sekaligus juga seorang guru besar. Dalam hubungannya dengan aspek politik, ia lebih sebagai konseptor daripada eksekutif. Hal ini terbukti dengan adanya pewarisan imamah kepada muridnya untuk memimpin seluruh pesantren Tarajumah. Kalau imamah tidak menonjol berarti pendekatan konsultatif lebih penting dari pada pendekatan instruktif dalam kehidupan organisasionalnya.
Mungkin itulah sebabnya maka sejak semula dalam kalangan santri Tarajumah tidak banyak terpikir untuk membentuk organisasi formal bagi ketarajumahannya.
Bagi keluarga Tarajumah, K.H. Ahmad Rifa’i terasa sebagai guru dan bapak, bukan sebagai pemimpin spiritual seperti pada aliran kepercayaan. Dengan demikian tidak terasa adanya eksklusivisme terhadap muslim lainnya, yang agak terasa hanyalah adanya semacam distinctive feature saja. Rasa perbedaannya hanya seperti beda antara anak-anak bapak dengan anak-anak paman dengan kakek nenek yang sama dalam masyarakat Islam.
Tentang istilah, gerakan Rifa’iyah lebih tepat kiranya untuk menyebut aktivitas mereka sesudah adanya YPIR, sedangkan untuk aktivitas yang dilakukan K.H. Ahmad Rifa’i dan pengikutnya secara umum mungkin lebih tepat digunakan istilah Pesantren Tarajumah Rifa’iyah.
Daftar Pustaka
- Ahmad Adaby Darban. 1987. Rifa’iyah. Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah 1850–1982, Tesis S2, Fak. Sastra UGM Yogyakarta.
- Ahmadir-Rifa’i. 1266 H. Ri’ayatul-Himamah, manuskrip.
- 1990. Serat Cebolek dan Mitos tentang Pembangangan Islam, dalam Ulumul Qur’an. ISAF, Jakarta, no. 5 Vol. II.
- Sartono Kartodirdjo. 1973. Protest Movements in Rural Java. Oxford University Press, Oxford.
- ———, et al. 1975. Sejarah Nasional Indonesia, jld. IV. Dept. Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta. a.
Oleh: Drs. Hasyim Asy’ary, MA (Dosen UGM Fakultas Sastra pada 1990), disampaikan dalam Seminar Nasional “Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie, kesinambungan dan perubahannya” yang diselenggarakan di Balai Kajian Sejarah Yogyakarta tanggal 12–13 Desember 1990
Penulis: Hasyim Asy’ary
Editor: Ahmad Zahid Ali
Sumber: Dokumentasi Seminar Nasional “Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX Gerakan Kiyai Haji Ahmad Rifa’ie, kesinambungan dan perubahannya” dan youtube Rifa’iyah Media