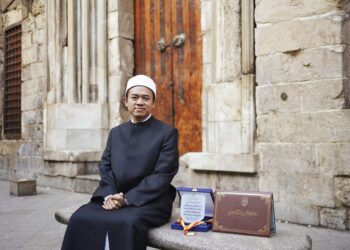Perlu kita sadari bahwa pola sejarah organisasi Rifa’iyah berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Sebagaimana Muhammadiyah ia lahir sebagai organisasi, kemudian disusul akumulasi jamaahnya dan dinamika budayanya. Artinya organisasi dulu, baru kemudian jamaah dan budayanya menyusul. Rifaiyah bisa dibilang jamaah dulu eksis baru kemudian organisasi (jamiyah) muncul setelah hampir dua ratus tahun kemudian.
Rifa’iyah diawali dari pesantren Kalisalak yang diasuh oleh KH. Ahmad Rifa’i. Murid-muridnya kemudian berjejaring di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat membentuk majelis ta’lim dan pondok pesantren. Sehingga budaya relasi Kiai dan santri sudah terbentuk terlebih dahulu, sebelum muncul gagasan organisasi. Budaya kepemimpinan organisasi yang mendasari keputusannya pada musyawarah dengan nuansa egaliter kadang bertentangan secara budaya dengan tradisi sowan ala pesantren, yang keputusan-keputusannya menunggu fatwa dan titah Kiai dan Bu Nyai. Maka kemunculan organisasi merupakan budaya baru yang penyesuaiannya butuh rentang waktu panjang, apalagi budaya organisasi menuju arah perubahan budaya kesetaraan dan keadilan. Pesantren dengan budaya feudal, artinya kepemimpinan dibatasi secara nasab, kadang bertentangan dengan budaya organisasi yang membuka peluang kesempatan bagi siapapun untuk memimpin.
Pesantren Kalisalak berdiri sejak 1835 telah membangun budaya masyarakat santri yang taat kepada seorang Kiai. Setelah K.H. Ahmad Rifa’i meninggal dunia, para murid pertamanya masih meneruskan dakwah di daerah asal masing-masing hingga memperoleh ikatan murid yang baru. Pada 1965, K. Carbin yang merupakan seorang tokoh Rifa’iyah sekaligus guru agama yang berasal dari Tanahbaya, Randudongkal, Pemalang, memprakarsai berdirinya sebuah organisasi dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Rifa’iyah (YPIR). K. Carbin merupakan sarjana pertama Rifa’iyah, dengan begitu masyarakat mempercayai Beliau untuk mengendarai YPIR.
Ide membentuk organisasi tersebut ditujukan juga dalam dunia pendidikan, agar dapat melakukan modernisasi Rifa’iyah yang pada periode 1960-an, khususnya Pondok Pesantren Rifa’iyah mengalami penurunan jumlah santri. Penurunan kuantitas tersebut salah satunya dipicu oleh kemunculan sekolah-sekolah formal dan madrasah-madrasah Islam yang telah dikelola secara modern. Hal itu mempengaruhi perkembangan pondok pesantren Rifa’iyah di beberapa daerah yang masih dikelola secara tradisional.
Pembentukan YPIR juga merupakan respon terhadap anggapan miring masyarakat luar Rifa’iyah yang menyangka bahwa jamaah ini membawa ajaran sesat. Juga tindak lanjut dari aspirasi internal jamaah yang menghendaki ‘Rumah Besar’ karena selama ini aspirasi Jamaah Rifa’iyah terombang-ambing diantara ormas dan partai lain.
Melihat berbagai hal tersebut, Rifa’iyah merasa perlu membentuk sebuah wadah untuk mengorganisir kegiatan jamaah. Oleh karena itu, Carbin sebagai pemrakarsa beserta dengan sesepuh ulama Rifa’iyah Tanahbaya diantaranya K. Hambali membentuk Yayasan Pendidikan Islam Rifaiyah (YPIR) pada 7 Mei 1965. Yayasan ini merupakan cikal bakal Rifa’iyah sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Sampai pada era tahun 90-an warga Rifa’iyah masih saja selalu ditimpa dengan anggapan miring tentang ajaran sesat, kesalahpahaman di masyarakat tentang rukun Islam satu, dalam shalat warga Rifa’iyah tidak berkenan makmum kepada non Rifa’iyah, Tajdidun Nikah, Keabsahan Wali Nikah, Qadha Shalat dalam shalat tarawih, sampai pernah terjadi khalaqah 100 ulama Jawa Tengah dalam rangka mengonfirmasi keabsahan ajaran Rifa’iyah.
Pada awalnya kesalahpahaman tentang Rifa’iyah itu telah dipantik oleh penjajah dan kolaboratornya ulama pribumi. Berdasarkan keterangan sejarawan NU Agus Sunyoto, bahwa persekusi para ulama berawal dari kebangkrutan pemerintah Belanda pasca perang jawa (1825-1830), maka strategi penjajahan fisik digantikan dengan penghilangan supremasi para pemimpin Islam, dengan cara memanipulasi karya sastra/sejarah dalam bentuk serat, dan babad.
Serat Cebolek berisi tentang penggambaran betapa hinanya KH. Ahmad Rifa’i dan K. Mutamakkin. Babad Kediri berisi tentang penggambaran rendahnya akhlak Raden Patah (Murid Sunan Ampel) yang menyerang Brawijaya V Raja Majapahit yang notabene ayah dari Raja Demak tersebut. Dalam Negarakertagama diceritakan tentang sosok fiktif Kenarok untuk menghinakan raja-raja Jawa yang mempunyai leluhur berkelakuan bejat.
Dalam manaqib Syaikh Ahmad Rifa’i diterangkan bahwa makam/petilasan di Batu Merah Ambon ditanami kepala babi/celeng oleh penjajah Hindia Belanda, sehingga sampai tahun 90-an masih beredar stereotype _mbudiyah matine dadi celeng._ Penjajah Hindia Belanda sadar bahwa kekuatan perlawanan pribumi terletak di figur pemimpinnya, sehingga pembunuhan karakter para pemimpin merupakan strategi yang harus dilancarkan.
Fakta sejarah tersebut kemudian mewariskan kesalahpahaman kepada sebagian masyarakat Indonesia terhadap KH. Ahmad Rifa’i dan Rifa’iyah (budiyah, tarajumah). Bahkan vibrasi kesalahpahaman tersebut masih bisa dirasakan hingga sekarang. Di antaranya baru-baru ini, beberapa teman memberi kabar bahwa pernikahannya terancam gagal, gara-gara diketahui bahwa dirinya warga Rifa’iyah.
Pada tahun 90-an Jurnal Ulumul Qur’an memuat tulisan-tulisan perihal serat Cebolek yang ditulis sejarawan Indonesia. Tulisan tersebut direspon oleh warga Rifa’iyah dalam edisi berikutnya yang menginspirasi lahirnya tabayun akbar tentang KH. Ahmad Rifa’i, sejarah dan ajarannya dalam penyelenggaraan Seminar Nasional Mengungkap Pembaharuan Islam Abad XIX. Gerakan KH. Ahmad Rifa’i perubahan dan kesinambunganya di Balai Kajian Sejarah Katamso Yogyakarta.
Seminar paling besar sepanjang sejarah ini menghasilkan rekomendasi di antaranya, mengangkat KH. Ahmad Rifa’i menjadi pahlawan nasional, membentuk ormas Rifa’iyah, sebagai rumah besar, dan legalitas. Pembentukan Rifa’iyah sebagai organisasi dimulai sejak Halaqoh Ulama Rifa’iyah Tarajumah di Pondok Pesantren Al-Islah Junjang Arjawinangun Cirebon. Disusunlah personalia Pengurus Pusat Rifa’iyah Tarajumah (RIFATARA). Terpilihlah KH. Muhammad Saud Arbai Cepokomulyo, Gemuh, Kendal sebagai Ketua Umum Rifa’iyah Tarajumah. Kemudian pada Muktamar berikutnya terpilih KH. Ali Munawir Ridwan sebagai Ketua Umum. Dan Lima Tahun berikutnya estafet kepemimpinan dinahkodai Oleh KH. Ahmad Syadzirin. Dalam kepemimpinan beliau mulai menginspirasi munculnya organisasi perempuan RIfa’iyah.
Diakui atau tidak, ide munculnya organisasi perempuan Rifa’iyah bermula dari tokoh organisasi Rifa’iyah, dan tokoh perempuan Rifa’iyah yang kebetulan berdomisili di Pekalongan. Setelah berdirinya organisasi Rifa’iyah pada tahun 1991, seorang Pimpinan Pusat Rifa’iyah KH. Syadzirin Amin mulai melakukan gerakan untuk menumbuhkan kesadaran perempuan Rifa’iyah di Pekalongan guna membentuk wadah organisasi. Saat itu KH. Syadzirin masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Rifa’iyah.
Di antara perempuan Rifa’iyah yang ikut dalam pertemuan-pertemuan bersama KH. Syadzirin adalah Ny Hj. Halimah (Bojong Minggir), Ustadzah Nur Hasanatul Karimah (Jajarwayang), Hj. Miskiyah (Jajarwayang), Ustadzah Asri Masrurah (Kesesi).
Menurut penuturan Hj. Halimah, beliau banyak mendapatkan motivasi dan dukungan dari mendiang KH. Syadzirin Amin, perihal gambaran organisasi perempuan Rifa’iyah ke depan. Ternyata motivasi itu turut mengusik Hj. Halimah dan perempuan Rifa’iyah di Pekalongan untuk berperan dalam organisasi, agama, dan masyarakat. Nantinya pendirian organisasi perempuan Rifa’iyah, mereka jadikan media dakwah dan menyebarkan kemanfaatan bagi halif.
Sesudah beberapa pertemuan dilakukan, akhirnya Hj. Halimah dan perempuan lainnya mulai tergugah untuk membentuk wadah organisasi perempuan Rifa’iyah di Pekalongan. Ny. Hj Halimah dalam menyalakan semangat berorganisasi tidak sendirian, di antara sahabat yang selalu bersamanya dalam berjuang diantaranya Nur Khasanatul Karimah dan Hj. Miskiyah. Sebenarnya, Karimah-lah yang pada awalnya paling semangat dalam melakukan konsolidasi dengan perempuan-perempuan Rifa’iyah di Pekalongan. Hj. Halimah, Hj. Miskiyah Ny. Asri Masrurah sesekali ikut membantu konsolidasi ke berbagai desa bersama Karimah dan perempuan Rifa’iyah lainnya.
Namun, semangat ini tak hanya tumbuh di pesisir utara Jawa. Di dataran tinggi Wonosobo, muncul semangat serupa. Himbauan KH. Syadzirin Amin juga sampai ke telinga perempuan Rifa’iyah di sana. Maka, pada tahun 1996, lahirlah organisasi perempuan Rifa’iyah bernama Pemudi Rif’ah, yang selanjutnya menjadi Pemudi Rifa’iyah. Organisasi ini dipimpin oleh Ibu Istiqomah Azzain yang kemudian dilanjutkan Bu Nyai Isna Muflihatin, yang saat itu baru saja menyelesaikan masa nyantri di pesantren. Ia langsung memimpin gerakan ini dengan penuh dedikasi.
Keinginan mendirikan organisasi perempuan Rifa’iyah baru terwujud pada 8 September 2000 dengan membentuk IFARI (Ikatan Fatayat Rifa’iyah) atas prakarsa Nur Khasanatul Karimah. Dalam perjalanannya, organisasi ini mengalami pergantian nama dari IFARI menjadi RUMRI (Remaja Umroh Rifa’iyah), termasuk Pemudi Rifa’iyah Wonosobo, pada 11 Januari 2001. Setelah itu pada 3 Maret 2002 berganti nama lagi menjadi UMRI (Umroh Rifa’iyah) dengan asumsi merujuk kepada nama putri KH. Ahmad Rifa’i yang bernama Siti Umrah.
UMRI menjadi wadah kegiatan berorganisasi semua perempuan Rifa’iyah, tidak hanya sebatas wanita dewasa, tetapi juga mewadahi remaja putri. Sampai akhirnya pada 15 April 2016 nama organisasi ini berganti lagi menjadi Ummahatur Rifa’iyah (UMRI). Pergantian tersebut merupakan aspirasi kaum ibu dari beberapa daerah Rifa’iyah yang meresahkan perihal kepanjangan Umrah Rifa’iyah, karena seringkali publik menyangka bahwa nama Umroh Rifa’iyah sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIH), bukan sebagai nama organisasi perempuan Rifa’iyah.
Munculnya organisasi perempuan Rifa’iyah merupakan buah keberanian para perintisnya dalam menemukan solusi zaman terhadap dominasi peran perempuan yang selama ini sebatas pada peran domestik (rumah tangga). Kegiatan-kegiatan perempuan yang melibatkan peran-peran publik, interaksi dengan Lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi lain merupakan langkah perubahan-perubahan budaya. Mulai tumbuh kesadaran kemandirian ekonomi perempuan Rifa’iyah, kesadaran untuk berpendidikan formal tinggi, kesadaran perempuan untuk turut berkhidmah di sektor halif.
Pra berdirinya organisasi perempuan Rifa’iyah masih kentara paham-paham keagamaan yang menjadi halangan peran publik perempuan Rifa’iyah. Rifa’iyah sebagai paham yang dianggap mengutamakan ikhtiyat (kehati-hatian), sebagian doktrinnya masih mengutarakan perbedaan kedudukan perempuan dan laki-laki. Di antaranya mengenai perihal hukum suara perempuan yang masih kontroversial.
Diantaranya suara perempuan yang dianggap sebagai aurat dan tidak boleh terdengar secara umum atau terdengar oleh pria yang bukan muhrimnya. Ajaran ini katanya didasarkan pada kitab Tabyin al-Islah karangan KH. Ahmad Rifa’i yang juga senada dengan pendapat Imam Zarkasyi dan Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami. Mereka mengharamkan mengeraskan suara perempuan, khususnya dalam shalat dan mengharamkan mendengarkan suara perempuan apabila suara perempuan dapat menimbulkan syahwat bagi pria. Akibat paham yang demikian ini sempat muncul pelarangan-pelarangan ditampilkannnya grup rebana putri di majelis-majelis.
Bagaimana sebenarnya keterangan KH. Ahmad Rifa’i tentang perihal fatwa-fatwa tersebut. Pendapat Imam Zarkasyi dan jumhur ulama yang terdapat dalam kitab Tabyin al-Islah karangan KH. Ahmad Rifa’i tidak mengharamkan, tetapi memakruhkan ketika dalam shalat dan boleh ketika di luar shalat. Pendapat KH. Ahmad Rifai dalam kitab Tabyin al-Islah juga tidak mengeluarkan kalimat yang mengharamkan suara perempuan jika diperdengarkan oleh pria (Amin, 2020).
Tetapi KH. Ahmad Rifa’i menekankan bahwa, mendengar suara perempuan diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan fitnah atau mendatangkan nafsu saat mendengarnya. Tentu hal ini dapat mendatangkan banyak tafsiran dari para pengikutnya. Terkadang karena kehati-hatian, pemahaman perempuan tidak boleh bersuara di depan umum menjadi satu doktrin yang banyak disebarkan kepada kalangan perempuan Rifa’iyah.
Tahun demi tahun dengan adanya organisasi perempuan Rifa’iyah yang bernama Umahatur Rifa’iyah (UMRI) semakin membawa perempuan pada kegiatan-kegiatan publik. Yang dirasa hal itu penting karena peran perempuan Rifa’iyah menjadi membuka wawasan pemikiran dan keagamaan untuk turut berperan bagi kemajuan jamaah Rifa’iyah dan kemajuan bangsa Indonesia. Kegiatan publik bagaimanapun penting, tetapi sebagaimana pesan-pesan yang disampaikan para Guru, jangan sampai meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga.
Penulis: Ahmad Saifullah
Editor: Ahmad Zahid Ali