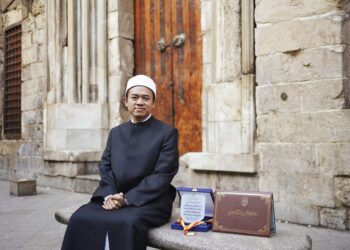“ikulah arep diseksekno temenan maring alim adil benere kawulangan.” (KH. Ahmad Rifa’i: Riayah al-Himmah)
Pagi itu di mushola pesantren masih remang, fajar belum terlihat hidungnya. Setelah semalaman di guyur hujan. Ocehan burung selalu menyapa telinga para santri di pondok pesantren. Seorang santri muda membuka kitab kuning dengan tangan sedikit gemetar. Di hadapannya, sang kiai menatap lembut, siap menyimak setiap huruf yang keluar dari bibir muridnya. Suara “qala Allahu ta’ala…” terdengar lirih, disambung koreksi halus dari sang guru. Begitulah sorogan berjalan: pelan, personal, namun dalam.
Bagi sebagian orang, metode ini mungkin tampak kuno — seolah tertinggal oleh hiruk-pikuk digitalisasi pendidikan. Tapi siapa sangka, para ahli neurosains modern justru baru sekarang membuktikan keampuhan cara belajar seperti ini.
Dari Otak ke Hati, dan dari Hati ke Otak
Mary Helen Immordino, Antonio Damasio, dua ilmuwan dari University of Southern California, dalam artikelnya “We Feel, Therefore We Learn” (2007), menemukan sesuatu yang mengejutkan:
Belajar bukan proses rasional murni. Ia adalah proses emosional.
Belajar tidak hanya membaca dan memahami makna, tetapi butuh senyuman Guru, Ketlatenan interaksi Guru-murid, Kesabaran bimbingan, dan ketabahan bersama dalam memahami. Belajar tidak hanya proses asah tetapi juga dinamika asih dan asuh.
Mary Helen Immordino, Antonio Damasio mempelajari pasien dengan kerusakan pada bagian otak yang mengatur emosi (prefrontal cortex). Para pasien ini masih bisa berpikir logis dan menjawab soal-soal dengan benar, tetapi mereka tidak bisa mengambil keputusan moral dan sosial dengan baik. Misalnya walaupun seseorang sadar bahwa ucapannya kasar, tetapi ia tidak bisa mengontrol lisannya, tidak bisa teposaliro apakah ucapannya menyakitkan hati atau tidak. Pengetahuan benar salah yang ada di kepala gagal untuk diamalkan. Pengetahuan mereka hidup di kepala, tapi mati di hati.
Dari situ Damasio menarik kesimpulan: “Tanpa emosi, logika tidak memiliki arah. Emosi adalah kemudi yang menuntun rasio.” Dan jika direnungkan, bukankah sorogan adalah wujud nyata dari kemudi itu?
Sorogan: Laboratorium Emosi dan Makna
Dalam sorogan, seorang santri tak sekadar membaca teks. Ia menyerahkan dirinya secara utuh pada bimbingan kiai. Ada naik turun emosi: rasa malu, segan, cinta, takut salah, ingin diperbaiki, dan bahagia ketika mendapat pujian.
Setiap koreksi bukan sekadar evaluasi kognitif, tetapi pengalaman afektif yang menancap di otak.
Menurut neurosains, emosi seperti ini mengaktifkan area otak prefrontal cortex dan hippocampus, bagian otak yang berperan penting dalam control emosi dan pembentukan memori jangka panjang. Artinya, pelajaran dalam suasana emosional bermakna akan bertahan lebih lama dalam ingatan daripada sekadar hitungan logis di kelas. Juga melatih lapisan layer emosional.
Ketika seorang santri ditegur halus oleh kiainya — “Nek maca ora usah grusa-grusu, sing tartil, ben mlebu neng ati,” — yang terekam bukan hanya bunyi kata, tapi suasana batin di balik ketulusan Sang Kiai.
Dari situ tumbuh bukan hanya kecerdasan berpikir, tetapi juga kecerdasan emosional.
Dari Individualisme ke Ikatan Spiritual
Sorogan juga menciptakan hubungan spiritual dua arah antara guru dan murid. Kiai bukan sekedar pengajar, tetapi Qudwah Kehidupan, (Role Model). Santri bukan sekadar pendengar, tetapi penimba ruh ilmu.
Immordino, dalam penelitiannya menyebut bahwa interaksi sosial yang bermakna membangun “emotional thought” — wilayah di otak tempat emosi dan kognisi menyatu.
Di sanalah tumbuh empati, motivasi, dan akhlaq Al-karimah.
Dengan kata lain, hubungan guru–santri dalam sorogan bukan sekadar proses akademik, melainkan pembentukan jaringan saraf sosial yang menanamkan nilai dan karakter.
Antara Zaman dan Zaman
Sekolah-sekolah modern sering mengira bahwa efisiensi berarti banyak siswa dalam satu kelas, satu guru, satu layar.
Tapi para ilmuwan kini menyadari bahwa kecepatan bukan segalanya — keterhubungan batin jauh lebih penting.
Sorogan telah mempraktikkan ini jauh sebelum istilah neuroeducation populer.
Ia menumbuhkan apa yang oleh psikolog modern disebut Self-Regulated Learning — santri harus mempersiapkan bacaan sendiri, mengoreksi diri, lalu siap diuji di hadapan guru.
Ada disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas belajar karena ingin diterima oleh guru dan oleh Allah.
Di dunia pesantren, belajar adalah ibadah. Dan neurosains kini justru membenarkan bahwa ketulusan dan emosi positif membuka jalur-jalur memori yang lebih dalam dan bertahan lama.
Belajar dengan Perasaan
Di ujung hari, ketika sorogan mengolah fikiran dan menuntun hati dalam dzikir, kita baru sadar bahwa pendidikan terbaik adalah yang menggerakkan hati sekaligus pikiran.
Sorogan mungkin tampak sederhana — seorang guru, satu kitab, satu murid.
Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi sistem pendidikan yang paling selaras dengan kodrat manusia sebagaimana dijelaskan neurosains modern:
- Emosi memberi makna,
- Makna menyalakan memori, dan akhlak
- Dan memori menghidupkan ilmu.
Maka, ketika dunia pendidikan modern sibuk mencari “metode inovatif”, pesantren diam-diam sudah mempraktikkan inovasi tertua dalam sejarah belajar: menjadikan ilmu sebagai pengalaman batin.
Penutup
Kita merasa, maka kita belajar –We feel, therefore we learn.
Dan di pesantren, rasa itu sudah lama diajarkan, di serambi kecil yang disebut sorogan.
Di sana, ilmu bukan sekadar data di otak, tetapi cahaya yang turun lewat hati yang lembut dan guru yang ikhlas.
Sorogan mungkin klasik, tapi justru di situlah letak kemodernannya: ia menyentuh sisi paling manusiawi dari belajar (perasaan).
Referensi
- Mary Helen Immordino-Yang and Antonio Damasio, 2007, We Feel, Therefore We Learn:
- The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education, (International Mind, Brain, and Education Society and Blackwell Publishing, Inc.)
Penulis: Ahmad Saifullah
Editor: Yusril Mahendra